Ketika Korban Berubah Status: Psikologi Ketidakadilan dalam Kasus Deli Serdang

Medan,WawasanRiau.com - Kasus di Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali memantik kegelisahan publik tentang wajah keadilan di tingkat akar rumput. Seorang pemilik toko ponsel berinisial PP, yang semula melaporkan pencurian, justru berakhir dengan status tersangka. Bagi publik awam, ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi soal rasa—rasa keadilan yang terasa jungkir balik.
Pihak Polrestabes Medan menegaskan bahwa penetapan PP sebagai tersangka tidak berkaitan dengan laporan pencurian. Polisi menyatakan perkara tersebut murni berasal dari laporan dugaan penganiayaan yang diajukan keluarga terduga pelaku pencurian. Secara normatif, penjelasan ini rapi: pencurian diproses di Polsek Pancur Batu, sementara dugaan penganiayaan ditangani secara terpisah.
Namun hukum tidak hanya hidup di atas kertas. Ia juga hidup di benak publik.
Dalam psikologi hukum, situasi ini dikenal sebagai role confusion—ketika seseorang yang secara moral merasa sebagai korban, tiba-tiba diposisikan sebagai pelaku. Pada titik ini, logika legal bisa benar, tetapi rasa keadilan sosial justru terguncang. Masyarakat bertanya: bagaimana mungkin orang yang tokonya dicuri justru berakhir duduk di kursi tersangka?
Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak bertindak di luar prosedur hukum saat menghadapi tindak pidana. Pesan ini sah secara normatif, namun problemnya lebih dalam. Dalam banyak kasus, warga kecil tidak selalu memiliki akses, pengetahuan, atau kepercayaan penuh pada mekanisme hukum yang ideal. Ketika emosi, amarah, dan ketakutan bercampur, respons spontan kerap tak terhindarkan.
Di sinilah negara seharusnya hadir lebih awal.
Kasus ini memperlihatkan jurang antara hukum formal dan keadilan substantif. Secara hukum, pencurian dan penganiayaan memang dua perkara berbeda. Tetapi secara psikologis, publik melihatnya sebagai satu rangkaian peristiwa: korban kejahatan yang kemudian justru terseret masalah hukum lain.
Jika negara gagal menjembatani jurang ini, yang tumbuh bukan kepatuhan, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa melapor ke polisi bisa berujung petaka. Ketakutan bahwa membela hak milik sendiri justru membuka pintu kriminalisasi.
Lebih berbahaya lagi, muncul pesan sosial yang samar tapi kuat: lebih aman diam daripada melapor. Dan ketika itu terjadi, hukum kehilangan fungsi preventifnya.
Kasus PP bukan hanya soal benar atau salah di meja penyidik. Ia adalah cermin relasi kuasa antara warga dan aparat penegak hukum. Negara perlu ekstra hati-hati agar penegakan hukum tidak terbaca sebagai penghukuman terhadap korban, meski secara yuridis perkara dipisahkan.
Tanpa sensitivitas itu, hukum memang berjalan—tetapi kepercayaan publik tertinggal jauh di belakang. Dan ketika kepercayaan runtuh, hukum tidak lagi dipatuhi karena diyakini, melainkan dihindari karena ditakuti. **


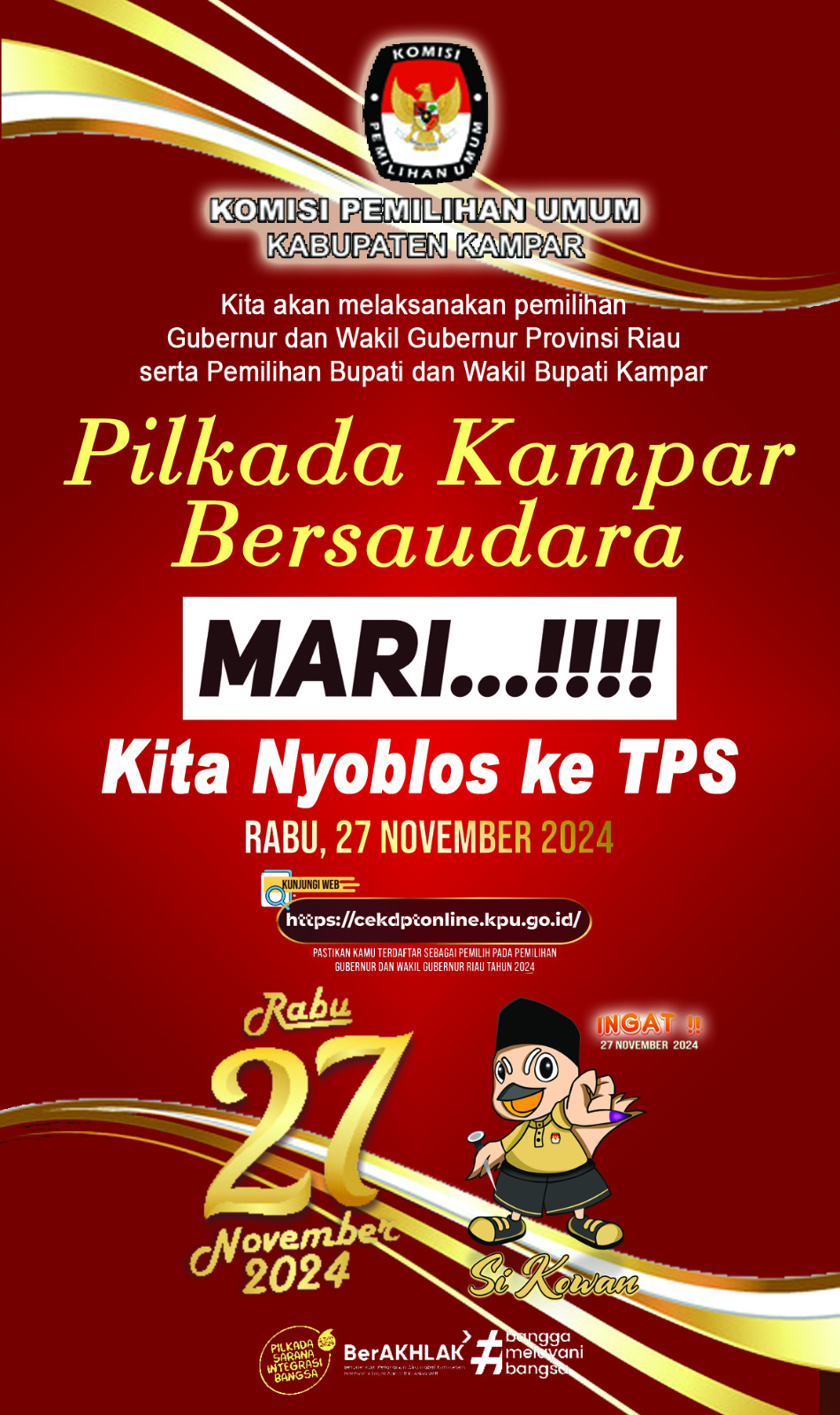




Tulis Komentar